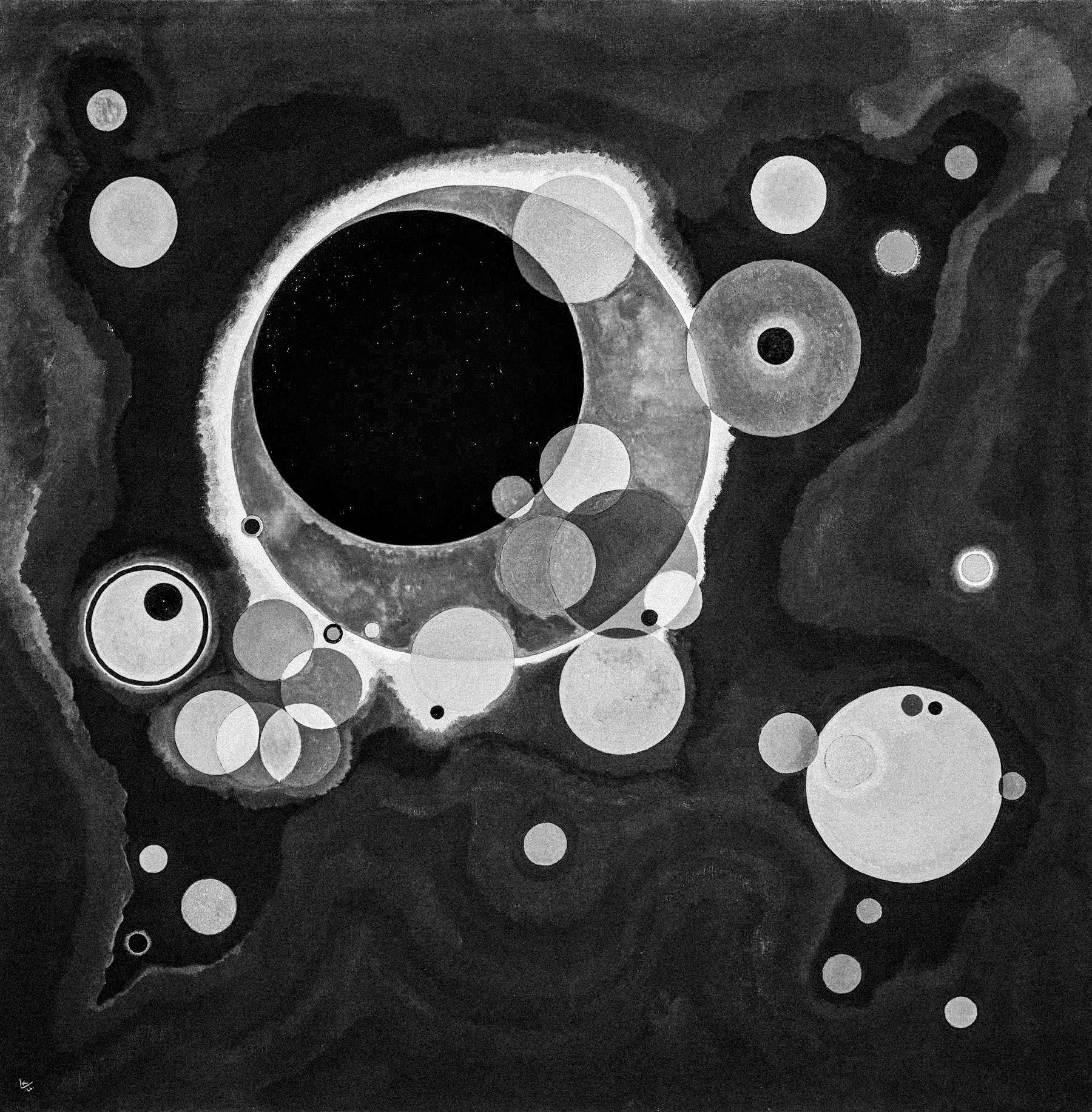Ale: “Kau sudah membaca berita?”Gori: “Berita apa? Ada triliunan berita yang diproduksi setiap hari.”
Ale: “Berita soal mantan pejabat intelijen Angkatan Udara Akirema Sorakit, yang menuding pemerintah negaranya menyembunyikan pesawat Alien sejak tahun sembilan belas tiga puluh-an. Kau percaya Alien?”
Gori: “Berita itu.... sudah. Begini, aku tak mau menggunakan kata 'percaya'. Terlalu dogmatis dan teologis. Aku tak suka pendekatan irasional semacam itu untuk menalar fenomena. 'Percaya' bukan satuan fisika. Tak saintifik. Tak ada beban pembuktiannya. Tak ada tolok ukur kebenarannya. Ya, alien... mungkin ada. Dan kalau pun ada, aku hanya mau percaya pada Alien yang bisa menari.”
Ale: “Sebentar, lantas apa yang kau percaya bila kau tak suka dan tak mau menggunakan kata 'percaya'?”
Gori: “Kalau pun aku mesti percaya, aku hanya mau percaya pada keskeptisanku.”
Ale: “Paradoks!”
Gori: “Lebih ke Paramex, sih.”
Ale: “Hahaha... Kembali ke topik. Kalau Alien ada bagaimana?”
Gori: “Kalau pun ada dan kalau boleh aku lebih konspiratif, aku malah curiga. Aku akan berlagak seperti seorang konspirator mulai sekarang… hmmm… jangan-jangan, lebih dari empat ribu dua ratus matriks yang ada di dunia ini dimungkinkan oleh semacam Alien dengan kecerdasan supertinggi tapi suka bercanda.”
Ale: “Kok bisa?”
Gori: “Ya bisa saja. Misalkan kita menggunakan drone berkamera dengan radius seratus meter untuk memantau bagaimana peradaban dari suku pedalaman di suatu pulau terisolasi yang sama sekali tak tersentuh teknologi. Sebut saja, suku Sontinol di Teluk Binggili. Gunakan asumsi yang sama. Tinggal diganti latar lokasi pemantauannya menjadi Bumi dan radiusnya jadi jarak Andromeda ke Bima Sakti. Katakanlah demikian. Bayangkan. Terbayang?”
Ale: “Sialan. Terbayang. Kepalaku seperti membeku.”
Gori: “Kemungkinan terbesarnya apa? Suku Sontinol, akan memandang drone itu sebagaimana kita memandang UFO.”
Ale: “Terkejut dan terheran-heran?”
Gori: “Tepat sekali! Ngerinya, dalam kondisi inosens-primitif yang kolektif semacam itu, juga terdapat kebolehjadian tinggi bahwa beberapa dari mereka yang skizoid akan mulai mendaulat dirinya sendiri sebagai utusan langit. Mereka akan mengaku pernah mendengar suara Alien, misalnya. Masalahnya timbul jika Alien itu bukan poliglot dan malah unilingual. Alias tak bisa banyak bahasa dan hanya bisa satu bahasa saja.”
Ale: “Misalnya bahasa apa?”
Gori: “Katakanlah, bahasa Preketek-preketek.
Ale: “Ok, lalu?”
Gori: “Bahasa ini akan mendapatkan legitimasi. Dipolitisasi sedemikian rupa dan cara. Misalkan dijadikan semacam bahasa liturgis dalam kidung ekstraterestrial pada ritus peribadatan di depan patung piring terbang.”
Ale: “Bangsat! Seram juga ya. Aku tak bisa membayangkan jika setiap sendi-sendi kehidupanku ditentukan oleh orang-orang naif yang percaya diri, yang bahkan tak bisa membedakan mana nyata mana delusi. Mana fakta, mana lulabi. Mana kebenaran, mana justifikasi. Ini terlalu ngeri, bahkan untuk sekadar dibayangkan dengan kadar kemungkinan sebesar lima persen.”
Gori: “Yang tak delusif dan bisa melihat peluang akan punya tendensi misionaris. Menjadi sales-mitos mengenai keberadaan Alien. Yang nyaris seluruhnya politis. Agar punya privilese. Entah ingin merasa lebih bersih, lebih tahu, demi lebih dikagumi dan disegani. Oleh siapa? Ya, sesamanya. Atau kalau mau ditarik lebih sosio-kultural, lebih kolonial, dan lebih eksploitatif... ya demi mengeruk sumber daya dari daerah jajahannya. Dengan apa? Sistem dan struktur pengetahuan. Beberapa dari mereka yang punya IQ lebih tinggi dari titik didih air dalam skala celsius mungkin akan menyerukan dekolonisasi pengetahuan. Masalahnya, mayoritas dari mereka hanya punya IQ setara titik didih air dalam skala fahrenheit. Imbesil. Aku bukan mau gaya-gayaan berlagak sok pintar. Aku cuma mau memuntahkan analisis kasar. Upaya meraba kebenaran yang sayangnya tak pernah peduli pada perasaan. Itulah alasan mengapa aku mengatakan demikian. Menarasikannya padamu. Biar ada teman. Aku tak mau mengalami kengerian sendirian. Siapa yang tahan?”
Ale: “Dasar bajingan! Eh, aku masih penasaran bagaimana nasib bahasa selain Preketek-preketek, katakanlah Prokotok-prokotok atau Prikitik-prikitik?”
Gori: “Ya, termarjinalkan. Dianggap rendah dan tak sakral. Tak mujarab. Tak punya kekuatan magis apa-apa. Pedahal uuaa, iiii, dan oooo yang disuarakan setiap komunitas suku pedalaman itu cuma soal variasi vokal belaka. Konvensi pula. Ada yang suka dan terbiasa mengucap huruf a, ada yang i, ada yang u, ada yang o. Cuma soal titik artikulasi di sepanjang rongga suara.”
Ale: “Yang cadel bagaimana nasibnya, ya? Misalkan ada mitos, untuk mencapai Lubang Putih mereka superwajib melantunkan mantra ekstraterestrial dengan enam ribu enam ratus enam puluh enam huruf 'r' setiap lima kali sehari. Mampus, sih. Plus, jika Alien yang mereka percaya punya anger issue. Mudah marah. Apalagi jika di Galaksi, tempat Alien itu bersemayam, tak ada psikiater. Atau sekadar psikolog yang tak bisa meresepkan obat. Sehingga, pada akhirnya, Alien itu tak bisa mengonsultasikan kemarahannya yang tak akan terjadi apabila ia tak berinisiatif tinggi untuk menciptakan suku-suku pedalaman. Yang cadel biologis. Lidahnya pendek atau kecil secara anatomis. Alien problematik itu akan terjebak pada tahap kedua, dari lima tahap kesedihan. Ya, kemarahan. Ditambah gemar mengancam dan pendendam. Kacau.”
Gori: “Kabar buruknya, penderitaan suku pedalaman yang cadel tak sekadar itu. Selain memengaruhi bagaimana berbicara, makan, dan menelan... kecadelan dapat menimbulkan komplikasi saat menyusu. Bayi cadel yang secara anatomis berlidah kecil dan pendek bisa kesulitan dalam menyusu. Ketika menetek, aih-alih mengisap, bayi itu malah mengunyah puting payudara ibunya. Hal yang terjadi setelahnya hampir bisa ditebak. Dahinya dikeplak!
Ale: “Hahahahaha... sulit juga ya membayangkan seorang cadel berbahagia. Lebih sulit dari membayangkan seorang pekerja yang bekerja dengan gaji bercanda dan terus berharap semesta bekerja untuknya, tapi faktanya semesta bekerja di bawah tekanan.”
Gori: “Hahaha... sulit itu akan berkali-kali lipat. Kuadrat. Jika kau tahu bahwa mereka yang berlidah pendek akan bekerja lebih ekstra untuk menjulurkan lidah sehingga akan susah mengucapkan huruf 't', 'n', dan 'l'. Dengan demikian, mereka hampir tak bisa mengeluh dan memisuh dengan kata kasar seperti Kantal! Kkkkkk... aku tertawa seperti orang Silbra.”
Ale: “Hahahaha... cukup intermesonya. Menurutmu, apalagi yang ngeri dari mitos mengenai Alien-Alien itu?”
Gori: “Yang tak kalah ngeri begini... hanya karena perbedaan kata atau istilah untuk menyebutkan benda, sifat, peristiwa, tempat, terjadi adegan panah-panahan antar suku pedalaman yang sebenarnya membicarakan hal yang sama. Tambah ngeri kalau mereka berdarah dingin, sehingga mata panahnya diolesi batrakotoksin. Yang cukup untuk membunuh sepuluh manusia dewasa.”
Ale: “Barangkali karena di hutan belantara hanya ada katak panah beracun. Tak ada dokter THT yang bisa menyembuhkan masalah pendengaran. Sehingga, ketika terjadi kebudekan kolektif, puncaknya hanyalah peperangan. Secara lebih luasnya, dengan kapak perimbas, tombak berujung batu, pedang beraksara Preketek-preketek, senapan angin, senapan mesin, bom atom, hingga rudal balistik berhulu ledak nuklir.”
Gori: “Mengapa aku malah membayangkan Boothevon pergi ke dokter THT, ya?”
Ale: “Tanpa berobat saja, ia bisa menciptakan instrumen indah dan surgawi seperti Piano Seniti Nomor Empat Belas. Minimal Boothevon pakai cotton bud, deh. Maka tak diragukan lagi, ia akan menjadi komposer terbaik sepanjang masa. Setelah Chepin dan Dobussy, tentu saja.”
Gori: “Benar juga. Aku sepakat soal itu hahahaha... Omong-omong, aku sih suka instrumen Hins Zammor. Latar lagu film Antorstollir yang epik dan bikin suasana tambah sinematik itu. Tapi kalau mau kembali membahas lebih lanjut soal kecurigaanku bahwa empat ribu dua ratus matriks merupakan ulah semacam alien dengan kecerdasan supertinggi tapi suka bercanda, maka suku-suku pedalaman tak tersentuh teknologi itu, dapat kita asumsikan sebagai masyarakat primordial.”
Ale: “Ya aku tahu instrumen itu... Menarik... Ayo kita bahas lagi. Sebentar, masyarakat primordial?”
Gori: “Iya, salah satu fase paling awal. Biasanya, secara sosiologis, ada tiga ciri utama. Pertama, punya fetis terhadap benda kosmik... sebut saja batu meteor. Kedua, menyembah Alien berjumlah banyak. Ketiga, menyembah Alien yang tunggal. Ada ribuan alasan gaib di balik fenomena kefetisan dan penyembahan itu. Misalkan... mereka percaya bahwa batu meteor itu adalah batu ajaib yang diberikan Alien kepadanya. Hal ini tak akan terjadi apabila Alien punya kepribadian introver. Bukan ekstrover. Tidak narsis. Tidak minta validasi. Idih najis.”
Ale: “Abi! Anak babi! Serius dululah barang sebentar. Ada pertanyaan menggelisahkan di dadaku. Menurutmu, mengapa suku pedalaman di suatu pulau terisolasi yang tidak tersentuh teknologi bisa sebarbar itu?”
Gori: “Barangkali begini... Aku pakai 'barangkali' bukan untuk mengajak berpikir abstrak. Sesederhana karena aku belum bisa memastikan secara pasti. Masih hipotesis, belum kokoh jadi bangunan teoretis. Begini, di dalam batok manusia itu ada otak reptil. Letak spesifiknya di amigdala. Lapisan paling purba dari otak yang bertanggung jawab atas sembilan puluh persen pengambilan keputusan. Sejak kira-kira dua juta tahun lalu, ketika berburu-meramu, otak reptilian digunakan untuk bertahan hidup. Mengontrol kebutuhan dan ketubuhan dasar. Antara lari dan hadapi. Antara hidup dan mati. Produk evolusi hingga hari ini.”
Ale: “Bahaya juga, ya, warisan evolusi ini. Dilematis, sih. Ada baik, ada buruknya. Ya, klise.”
Gori: “Di zaman mahabeli seperti saat ini, otak reptil ibarat biang kerok yang tak kasat mata di balik mengapa banyak orang bertindak konsumtif. Secara neuroekonomi, saat berbelanja, konsumen sebenarnya tak memutuskan secara rasional, mereka hanya berpikir mereka melakukannya. Membanjirnya pilihan-pilihan dan perbandingan produk, misalnya Aypon vs Androit, memaksa otak reptil bertindak cepat. Mirip ketika dulu, kala Pleistosen, nenek moyang kita yang hidup di Akirema Aratu dan Natales, dihadapkan dengan Smilodon, sejenis kucing bergigi pedang. Pilihannya cuma dua. Dulu, lari atau hadapi. Kini, beli atau tidak. Keduanya sama-sama seperti pilihan hidup atau mati.”
Ale: “Orang gila. Kok bisa kepikiran?”
Gori: “Aku berpikir, maka aku kepikiran.”
Ale: “Overthinking, nggak sih?”
Gori: “Lebih ke oversinting, sih.”
Ale: “Hahahaha.... sebentar aku lupa menanyakan ini. Menurutmu, kalau Alien ada, bagaimana wujudnya?”
Gori: “Barangkali sama seperti gambaran umum di film-film dan komik-komik. Bermata besar, berpipi tirus, dan berambut botak. Tapi bagaimanapun rupanya, ciri morfologis seperti ini, berpotensi berujung pada pengultusan. Artinya, yang bermata kecil, berpipi gembil, dan berambut gondrong, akan cenderung dianggap tidak keren. Lebih ke tidak ilahi, sih. Tidak ada unsur ekstraterestrialnya. Maksudku.”
Ale: “Menarik. Ok, pertanyaan selanjutnya. Menurutmu, bagaimana nasib empat ribu dua ratus matriks ketika manusia mampu mengolonisasi planet lain, Mars misalnya?”
Gori: “Pertama, pendaratan Noil Armstreng dan Buzz Aldran di Bulan pada tahun Sembilan Belas Enam Sembilan dalam misi Ipelle Sebelas tak akan lagi dianggap sebagai akal-akalan NISI. Begitu pula Yura Gigiran. Dan Liyki, anjing pertama yang ke luar angkasa. Dan lainnya. Kedua, orang-orang akan mulai hidup dengan damai. Seperti gambaran Jehn Lonnen dalam lagunya, Imejin.”
Ale: “Imejin ders no hepen... its isi if yu trai... no hell bilow as... abop as, onli skai... imejin oll de pipel... lipin for tudei... ah... imejin ders no kantris... itis nat hard tu du... nating tu kill or dai for... en no relijien tuu... imejin oll de pipel... livin laif in piss... yu hu uuuu...”
Gori: “Yu mei sei am eu drimer... bat am nat de onli wan... ay hop somdei yu join as... en de woeld will bi as was.”
Ale: “Bagaimana kalau Alien tak ada?”
Gori: “Kalau Alien tak ada, barangkali orang-orang akan mulai percaya bahwa tiga ribu tahun lalu Piramida Gazi dibikin oleh orang-orang Rimes Kuno. Atau bahwa Stenohongo di Silasbury dibuat oleh para pemburu-pengumpul pada Mesolitik Awal. Seperti yang dikemukakan para arkeolog dengan bukti-bukti arkeologi. Bukan teori konspirasi yang didapat dari seorang tolol ketika buang air besar di kamar mandi. Walau bagaimanapun, kita masihlah bocah yang membuka buku bergambar demi memahami bagaimana bintang-bintang nun jauh di sana bekerja.”
Ale: “Kini, kau telah menjadi Kehidupan, penghancur Pascakematian!”
Gori: “Begini, aku bukan Epponhoimor. Aku tak berhasrat mengotaki pemboman Hareshami dan Nigisika. Aku lebih mau menjadi kucingnya Schrëdingor. Yang bisa bereksperimen pikiran. Tanpa harus dipusingkan dengan meningkatnya harga whaskis.”
Ale: “Ini serius, aku lupa bertanya... apa cita-citamu?”
Gori: “Astronot.”
Ale: “Yang benar saja!”
Gori: “Apa aku sedari tadi terdengar seperti seorang pemabuk bermulut besar yang sedang membual?”
Ale: “Tidak.”