Dewasa ini, setiap sendi kehidupan masyarakat bergerak dengan serba cepat—tak terkecuali industri fesyen dan berbagai geliat mode yang melingkupinya. Baru-baru ini, melansir dari CNN Indonesia, ada semacam kategorisasi citra diri dari cara berpakaian seseorang, khususnya kaum hawa: Cewek Mamba, Cewek Kue, dan Cewek Bumi.
Secara garis besar, sederhananya: Cewek Mamba adalah seorang perempuan yang berpakaian serba hitam; Cewek Kue adalah seorang perempuan yang berpakaian dengan warna-warna cerah, misalnya, kuning dan merah; Cewek Bumi adalah seorang perempuan yang berpakaian dengan earth-tone (warna-warna bumi), misalnya, cokelat, abu-abu, dan hijau tua.
Penulis hanya akan menganalisis secara umum (tak spesifik pada gender perempuan) serta singkat tipe yang pertama saja. Sebagaimana gaya hidup, pakaian mempunyai makna—baik secara sosial maupun personal. Makna, dapat ditelisik melalui beberapa pendekatan.
Semiotika
Menurut Derrida, seorang filsuf bahasa, semua ide-gagasan terkandung dalam bahasa dan tak ada seseorang pun yang mampu keluar dari bahasa. Jika pakaian adalah semacam metode komunikasi untuk mengomunikasikan sesuatu, maka dengan paradigma yang sama, dapat diasumsikan bahwa tak memakai pakaian pun merupakan suatu metode komunikasi, suatu cara untuk mengomunikasikan suatu pikiran atau perasaan (bahasa). Lantas, apa bahasa yang ingin dikomunikasikan seorang-mamba?
Hitam, adalah warna yang lekat dengan kegelapan, kesedihan, kedukaan, kematian, keeleganan, dan kemisteriusan. Seseorang yang berpakaian serba hitam, dengan demikian, memiliki kecenderungan untuk menandai dirinya sebagai individu yang “gelap”, sedang bersedih, sedang berduka, sudah menerima “mati”, mencoba elegan, dan penuh misteri. Dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut mencoba membangun tanda diri melalui atribut-atribut sifat yang dilekatkan pada warna hitam.
Saussure, seorang ahli bahasa dan tokoh strukturalis, menyatakan bahwa suatu tanda tak hanya ada dalam bentuk citra bunyi, tetapi juga dalam pemahaman. Seekor tokek disebut tokek karena ia memiliki citra bunyi “tokek”—sedangkan seekor kecoak tak memiliki memiliki citra bunyi “kecoak”, tetapi diberikan nama kecoak di atas persetujuan bersama bahwa hewan yang sering hidup di kamar mandi kotor tersebut dinamakan kecoak. Apa hubungannya dengan seorang-mamba?
Tentu saja seorang-mamba tak memiliki citra bunyi yang sama seperti seekor spesies ular endemik Benua Afrika bernama Black Mamba. Pointnya adalah bahwa segala sesuatu yang “ada” (besar kemungkinan) tak bisa lepas dari relasi tanda, penanda, dan petanda. Hitam adalah penanda (signifier) dan hal-hal yang identik dengan warna hitam (kegelapan, kesedihan, kedukaan, kematian, keeleganan, dan kemisteriusan) adalah petanda (signified). Ketika seseorang mengatakan kegelapan, kepala kita akan memiliki kecondongan untuk membayangkan warna hitam, begitu pula sebaliknya. Ini (mungkin) adalah bukti betapa kita terobsesi dengan relasi antara Penanda dan Petanda.
Fenomenologi
Selain tak bisa kabur dari bahasa, manusia pun tak bisa lepas dari fenomena. Fenomenologi, adalah ilmu yang mengkaji fenomena dan kesadaran sekaligus aliran filsafat yang berisi diskursus mengenai hal-hal personal (dan khusus) seperti pengalaman. Husserl, seorang filsuf sekaligus Bapak Fenomenologi, menekankan bahwa untuk memahami sebuah fenomena seseorang harus menelaah fenomena tersebut apa adanya. Seseorang harus menyimpan sementara atau mengisolasi asumsi, keyakinan, dan pengetahuan yang telah dimilikinya tentang suatu fenomena.
Dalam konteks Fesyen Mamba, penulis adalah seorang-mamba yang secara langsung mengalami fenomena tersebut. Jika dikorelasikan dengan kesuraman pandemi tak bertepi yang dirasakan secara pribadi, secara sosial, maupun secara global—ditambah survei yang dilakukan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI): pada tahun 2020, sebanyak 63 persen responden mengalami cemas dan 66 persen responden mengalami depresi (akibat pandemi COVID-19)—penulis menilai bahwa tren Fesyen Mamba mungkin hanyalah konsekuensi logis dari keadaan pandemi—di mana banyak orang kehilangan, berduka, bersedih, dan kemudian melupakan emosinya tersebut dalam cara berpakaian.
Fesyen Mamba, secara lebih luas, juga identik dengan seorang pelayat, à la gothic, dan secara sekilas mirip dengan gaya busana orang-orang dari gerakan Eksistensialisme Prancis tahun ’60-an yang membawa “wabah depresi” kepada dunia.
Sosio-Kultural
Tradisi Barat menganggap hitam sebagai warna ancaman dan pemberontakan—mereka mengasosiasikannya dengan kematian, pemakaman, kekuasaan, intimidasi, dan kontrol. Sehingga para Anarkis (seorang penganut Anarkisme: ideologi yang menentang hierarki dan status quo, khususnya negara) lekat dengan atribut pakaian serba hitam. Akan tetapi, dalam budaya kontemporer, orang-orang Barat melihat ‘hitam’ sebagai warna yang berkelas dan tanda dari suatu fesyen papan atas.
Secara sosio-kultural Timur, khususnya Indonesia secara garis besar, warna hitam dianggap sebagai jenis warna yang sakral. Warna hitam kerap digunakan dalam berbagai jenis pakaian kebesaran, seperti pakaian kerajaan, sampai busana pengantin. Pakaian berwarna hitam tak selalu negatif—dengan kata lain, situasional—bahkan positif, misalnya bagi seseorang yang sedang berziarah atau melayat, memakai pakaian berwarna hitam bermakna “baik”—ikut berduka dan menghargai keluarga yang sedang berduka.
Menurut interpretasi penulis, alih-alih tren yang berangkat dari faktor kesakralan sosio-kultural warna hitam, tren Fesyen Mamba, lebih merupakan gerakan selera personal bernuansa melankolisme-gelap—yang pada gilirannya menjamur secara kolektif karena kesamaan “rasa” di bawah pesimisme-pandemik yang dirasakan secara global. Mungkin juga karena memang seorang-mamba hanya sekadar menyukai warna hitam. Di sisi lain, analisis semiotik bertendensi menghiperbolakan suatu fenomena sosial yang sebenarnya biasa saja. Kita tutup dengan tafsiran de Waelhens atas pemikiran Merleau-Ponty, filsuf ambigu itu, bahwa dunia/realitas tak akan pernah bisa direduksi menjadi satu makna belaka—sebab dunia/realitas sungguhlah rumit. Kedwiartian? Kebanyakartian? Kebanyakan-arti?
*****
Referensi:
de Saussure, Ferdinand. 1998. Course in General Linguistics. Open Court;
Derrida, Jacques. 1997. De la grammatologie. Johns Hopkins University Press;
Husserl, Edmund. 1999. The Idea of Phenomenology. Springer;
de Waelhens, Alphonse. 1951. Une philosophie de l’ambiguïté. Publications Universitaires de Louvain;
Kaiser, S. (2011). The Semiotics of Clothing: Linking Structural Analysis with Social Process. In T. Sebeok & J. Umiker-Sebeok (Ed.), The Semiotic Web 1989 (pp. 605-624). Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110874099.605;
Smith, J. A., & Osborn, M. (2015). Interpretative phenomenological analysis as a useful methodology for research on the lived experience of pain. British journal of pain, 9(1), 41–42. https://doi.org/10.1177/2049463714541642;
Cherry, Kendra. 2020. verywellmind. “The Color Psychology of Black” https://www.verywellmind.com/the-color-psychology-of-black-2795814;
Tim CNN Indonesia. 2022. CNN Indonesia. “Viral Cewek Kue, Cewek Mamba, Cewek Bumi, Apa Sih Artinya?”. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220715071236-277-821821/viral-cewek-kue-cewek-mamba-cewek-bumi-apa-sih-artinya).

,_John_Singer_Sargent,_1884_(unfree_frame_crop).jpg)
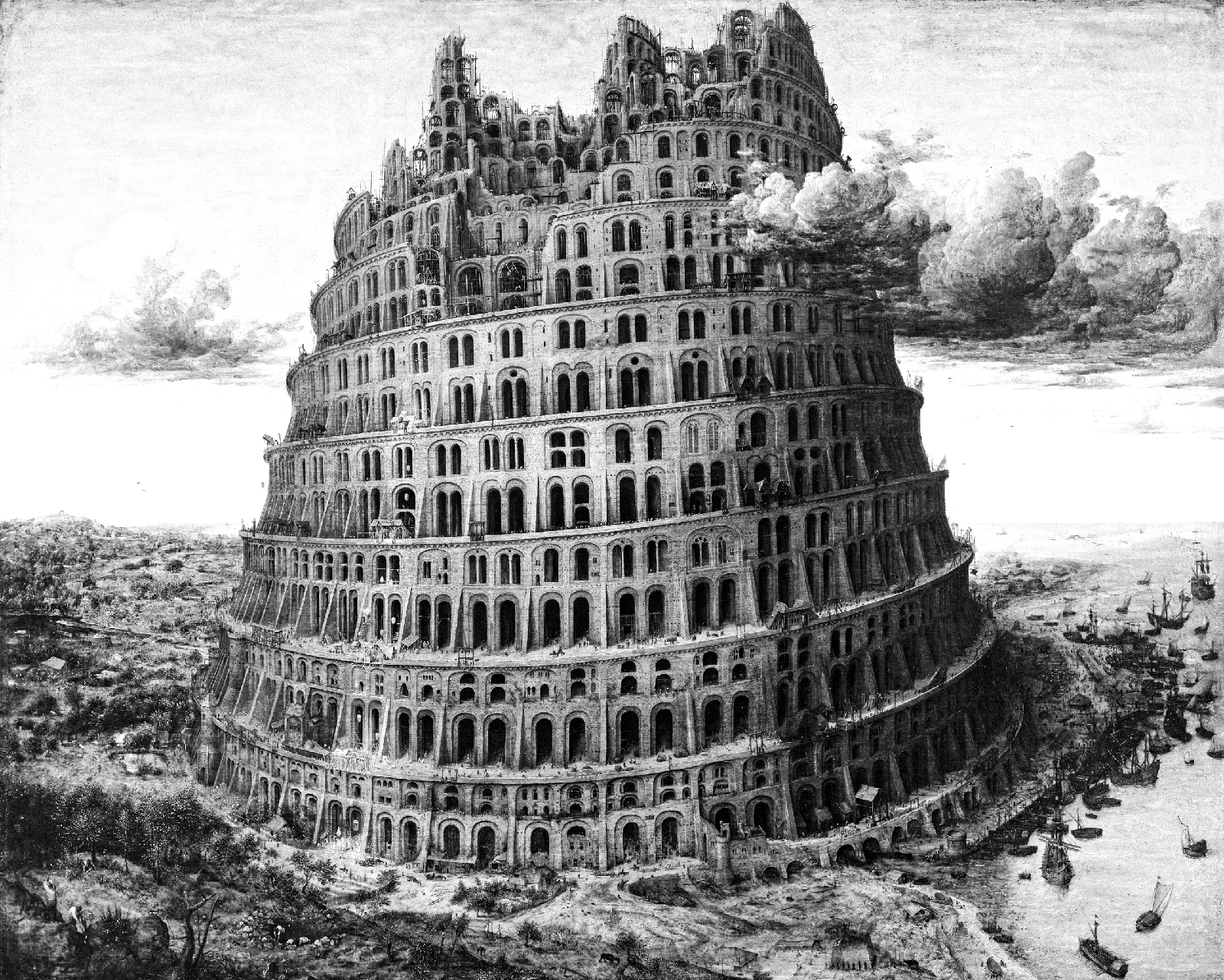





.jpg)
.jpg)