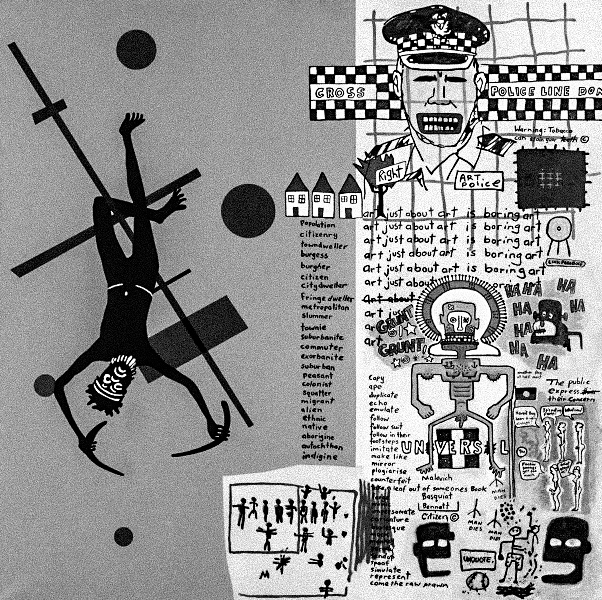terkadang aku membayangkan jika dilahirkan sebagai kuda liar di padang sabana; hanya berlari-lari, bebas, ke sana-ke mari & meringkik hihi-hihi. tak perlu sekolah, tak perlu bekerja, tak perlu menikah, tak perlu bertanya-tanya apakah ada kehidupan setelah kematian, tak perlu memikirkan: apakah kompleks Piramida Giza adalah ulah alien yang iseng ataukah sebuah bukti dari betapa jeniusnya nenek moyang umat manusia?
aku tak perlu meresapi betapa gabutnya Adam & Hawa ketika masih di taman surga. tak perlu merenungi betapa tersiksanya setan yang selalu dikambinghitamkan atas semua kejahatan. tak perlu berempati pada hewan yang kalah binatang ketimbang manusia. tak perlu memerhatikan manusia-manusia lain yang dewasa ini ditelan kanal-kanal media sosial. tak perlu menertawai betapa bloonnya orang-orang di Eropa sana sebelum Renaissance.
atau betapa susahnya Neanderthal membuat percikan api dari batu sekitar 50.000 tahun lalu. atau serumit apa metode komunikasi dari satuan bahasa sebelum adanya Lingua Franca. atau sesederhana apa bahasa yang digunakan di Menara Babel yang melegenda. atau kodifikasi macam apa yang mengikat penyair dalam semacam kredo Lisensi Puitika. atau betapa pentingnya lukisan bunga matahari yang dilukis van Gogh pada tahun 1887 bagi tradisi ilmu seni rupa.
atau betapa kesepiannya Darwin ketika 35 hari meneliti teori seleksi alam di Kepulauan Galapagos. atau betapa bingungnya Einstein menjelaskan Relativitas Waktu pada manusia yang tak pernah tepat datang tepat waktu. atau memantik mata kuliah semantik di kepala anak TK. atau betapa bersalahnya senyawa kimia arsenik ketika dipakai untuk membunuh seorang aktivis hak asasi manusia di atas udara. atau bagaimana rasanya meminum kopi campur sianida saat asam lambung sudah di depan mata.
betapa aku tak perlu memikirkan mengapa Hemingway bunuh diri sekitar 3 minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-62. atau mengapa orang-orang keren bunuh diri di umur 27 tahun. atau mengapa orang-orang naif selalu berumur panjang, sepanjang pertanyaanku, tentang mengapa kurikulum sejarah kita memfitnah bahwa Daendels tak membayar upah para pekerjanya dalam proyek jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1.000 kilometer jauhnya.
o betapa aku tak perlu mengingat betapa gobloknya Mao yang menyuruh warganya untuk membunuh sekitar 600 juta ekor burung gereja. atau betapa kacaunya Wabah Pes di Pulau Jawa. atau betapa mengerikannya bencana nuklir di Chernobyl, Ukraina. atau betapa rusuhnya peristiwa Tanjung Priok. atau pecahnya perang saudara di Amerika Serikat. atau mengingat-ngingat betapa berdarahnya Perang Salib atas nama agama. atau mengenang betapa jayanya Filsafat di kota Athena yang selalu tampak dungu di kepala orang-orang Sparta.
atau menafsir gelapnya kosmologi dari buku-buku yang berat itu. atau mengungkap siapa orang tolol di balik patung-patung Moai. atau ada apa di Area 51. atau mengapa Silicon Valley mengawali kedigdayaan AI. atau mengapa industri fesyen melaju dengan sangat cepat. atau mengapa skena musik indie bersinonim dengan senja, kopi, & puisi. atau mengapa pesatnya teknologi membuka lubang-lubang kelinci baru bernama depresi. atau mengapa pada akhirnya utopia berganti baju menjadi distopia.
atau mengapa orang-orang berjudi di Miraza. mengapa di Bogor hujan terjadi hampir setiap hari. mengapa di Afrika, panas & kelaparan adalah makanan sehari-hari. mengapa di Jalur Gaza, misil, rudal, & batu adalah kunci. mengapa di India, Kasta Dalit lebih rendah dari sampah. mengapa di Catalunya, kemerdekaan sama dengan halusinasi. mengapa di Selandia Baru, suku Māori menandai kepunahan Burung Moa. mengapa di Australia, umat manusia kalah perang dengan Burung Emu. mengapa di Kalimantan, Orang Utan kalah telak dari Orang Tambang.
atau menimbang-nimbang kemungkinan jika aku tak dilahirkan di tahun 2000. atau tak pernah dilahirkan sama sekali. atau mencari diriku sendiri yang sudah hilang bersama pandemi jahanam ini. atau mencari cara agar aku bisa secepatnya moksa, memutus rantai-karma, & meludahi semua omong kosong di atas simulasi samsara ini. atau pasrah dengan mengucap Lahaula Walakuata. atau Sabbe Sattā Bhavantu Sukhitattā. atau merapal mantra andalan seperti Amorfati; ya sudahlah mau bagaimana lagi.
o betapa aku ingin sekali berkata bahwa hidup berjalan seperti menaiki bianglala di pasar malam yang sudah tutup. & betapa aku ingin menggugat Tuhan: ya Tuhanku, jika hidup adalah adalah tanda baca; maka aku adalah tanda tanya yang tak akan pernah bosan menodong-Mu dengan miliaran pertanyaan—yang selalu berkembang biak dalam bekunya setiap jawaban dari-Mu
***
(ceritanya ganti adegan & tata bahasa)
mula-mula Thales berkata: semua berasal dari air & akan kembali ke air. diikuti dengan Anaximander yang berkata: semua berasal dari Apeiron, semacam sesuatu yang tak diketahui itu adalah apa. Hmmm seperti itu, begitu ujarku. lalu, Anaximenes berkata: semua berasal dari udara. tapi masa iya? begitu ucapmu. entahlah sayang, hanya Aang, Appa, Avatar Roku, & tukang kipas angin yang tahu.
tak mau kalah, Heraclitus berkata: semua berasal dari api. terdengar seperti doktrin-dogma Agama Majusi, begitu katamu sembari menatap tajam mata Freddie yang sedang menyanyikan lagu—tentang Galilei berjudul Bohemian Rhapsody. maka berbicaralah Zarathustra: aku hanya percaya pada Tuhan yang tahu caranya menari. Si Dinamit tersenyum, kemudian melakukan tarian sufi bersama Rumi sampai mati.
sedang Parmenides hanya berkata: realitas adalah lingkaran sempurna yang tak bergerak, terbagi, & berubah, singkatnya monoton. ya begitulah, sama, stagnan, & tanpa kemungkinan untuk mengembang. tapi sayangku, adakah seseorang yang menaruh rasa peduli pada perasaan Isaac Newton yang mengganti namanya menjadi Isaac Tangis—setelah kerangka statis alam semesta buatannya, dihantam Planck bersama kenyataan bahwa alam semesta memang terus mengembang.
tapi alam semesta memang mengembang, sayang. seperti roti yang diberi baking powder. & Einstein memenangkan tender ilmu pengetahuan. & Fisika Klasik berganti baju menjadi Mekanika Kuantum. persis seperti dosis obat lithium karbonat yang sengaja kuganti dengan mencium keningmu setelah melalui hari-hari yang bangsat, rindu-rindu keparat, makna-makna hidup tanpa alamat, & mood-swing yang laknat. lupakan, mari kita berpindah ruang-waktu.
pagi itu, kita melihat abad-abad Pencerahan di Eropa ditandai dengan Descartes yang berujar: Cogito Ergo Sum; aku berpikir, maka aku ada. di sore hari kita melihat Camus dengan gebrakannya: Je Me Rebelle Donc J’existe; aku berontak, maka kita ada. ketika malam tiba, kita menyaksikan masyarakat konsumer di zaman kontem-pler berseru: aku belanja, maka aku ada. esoknya kita terbangun oleh suara-suara bising digitalisasi: Selfito Ergo Sum; aku selfie, maka aku ada. & langsung panik mendengar sangkakala alterasi-budaya: Covido Ergo Zoom; aku covid, maka aku zoom.
apa itu ada? sedang Siti Jenar berkata: ada adalah tiada & kekosongan ini bernyawa. apa itu ada? kata Hegel di The Phenomenology of Spirit yang tak pernah selesai kubaca. apakah ada itu tak ada maknanya? serupa mencari rasio emas di zaman perunggu. pencarian ini takkan merubah kenyataan bahwa kita “Too Poor for Pop Culture” seperti yang pernah dituliskan D. Watkins & digaungkan kembali oleh F. Stevy.
tanyakan saja pada seekor kucing yang diletakkan di sebuah kotak tertutup bersama sebuah botol berisi racun sianida. pertanyaannya, apakah kucing itu masih hidup? nyatanya Schrödinger muak dengan semua omong kosong ini, lalu menelurkan bahasa:
G G
G G
G G
G G
G G
G G
G
G
G
G
G
G
G
(2021)