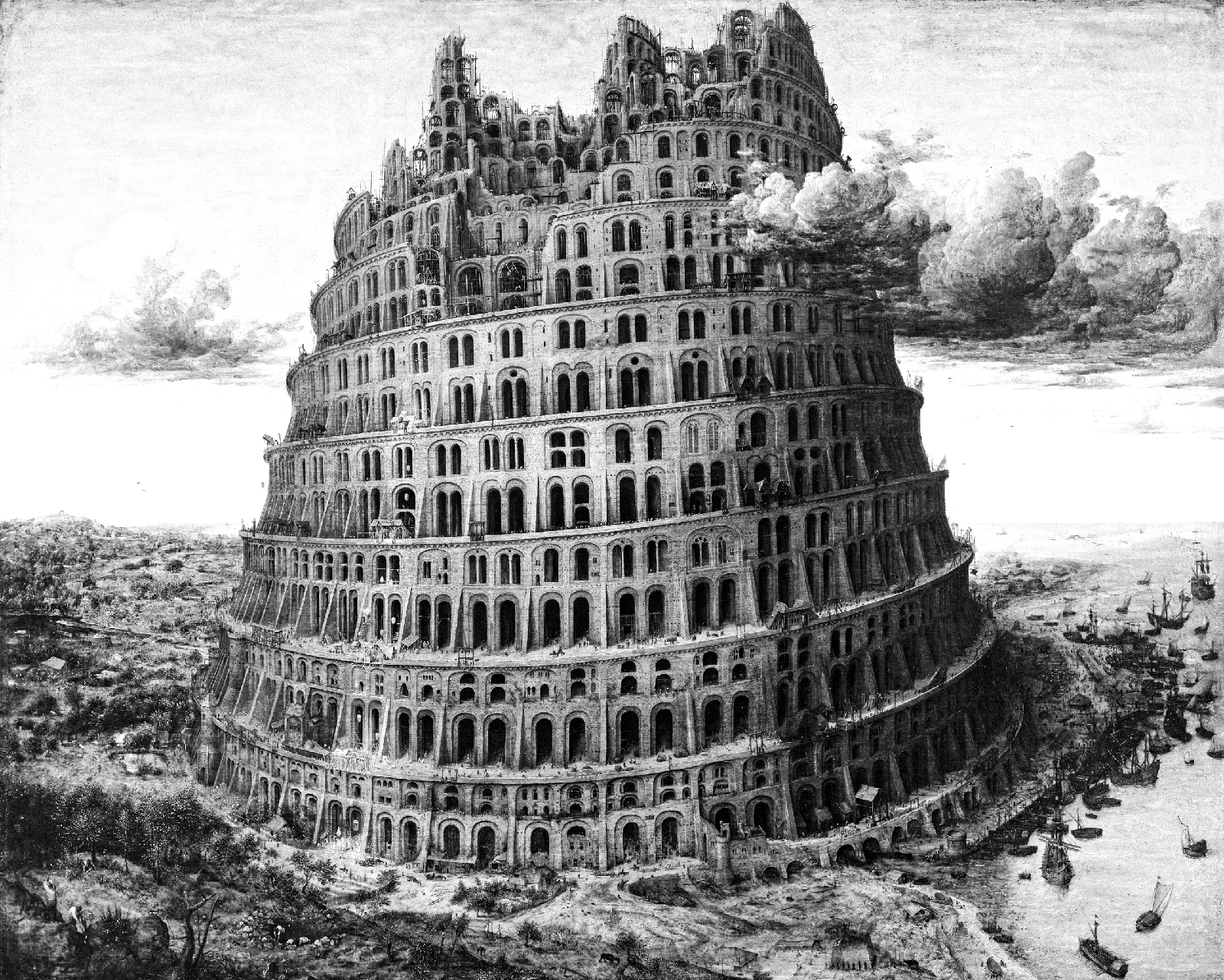Sunday 29 January 2023
Friday 23 December 2022
Batas-Batas Bahasa dalam Filsafat Wittgenstein (Esai Translasi)
Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) adalah salah satu filsuf terpenting abad ke-20. Wittgenstein tak hanya menyumbang pemikiran krusial dalam diskursus tentang bahasa, logika, dan metafisika, tetapi juga dalam etika—cara kita hidup di dunia. Dia menerbitkan dua karya signifikan: Tractatus Logico-Philosophicus (1921) dan Philosophical Investigations (1953), yang melambungkan namanya. Kedua buku ini adalah kontribusi besar bagi filsafat bahasa abad 20.
Wittgenstein memiliki kepribadian yang begitu sulit dipahami. Mereka yang mengenalnya (mungkin akan) mengira apakah dia adalah orang gila ataukah seorang jenius. Wittgenstein dikenal karena membuat dirinya sendiri frustrasi—seperti seseorang yang mondar-mandir di suatu ruangan mengutuki kebodohannya sendiri, dan menyumpah-serapahi para filsuf karena kebiasaan mereka mengikat diri mereka sendiri dalam “simpul-simpul semantik”. Dalam kerendah-hatiannya, Wittgenstein tidak takut mengakui kesalahannya sendiri. Dia pernah berkata: “Jika orang tak pernah melakukan sesuatu yang bodoh, tak ada kecerdasan yang akan didapatkan”. Dia juga berkata: “Aku tak tahu mengapa kita ada di sini, tetapi aku cukup yakin itu bukan untuk bersenang-senang”. Wittgenstein adalah seorang dosen dan para mahasiswa mengikuti kelasnya di Universitas Cambridge dengan gemetar, tak pernah yakin apakah mereka akan menyaksikan tindakan brilian dari dekonstruksi-logis atau ledakan dari pikiran yang tersiksa.
Terkadang krisis memicu produktivitas. Wittgenstein, yang terus-menerus berada dalam cengkeraman semacam “bencana intelektual”, cenderung memajukan pemikirannya dengan menyanggah apa-apa yang sebelumnya mapan dan dia anggap benar. Contoh terbaiknya adalah hal yang membuatnya terkenal, menyatakan “nature bahasa”. Dalam Tractatus, Wittgenstein mengemukakan teori representasional dari bahasa. Dia menggambarkan ini sebagai The Picture Theory: realitas (‘dunia’) adalah kumpulan fakta-fakta yang begitu banyak yang dapat kita gambarkan dalam bahasa, dengan asumsi bahwa bahasa kita memiliki bentuk logis yang memadai. “Dunia adalah totalitas fakta-fakta, bukan benda-benda” kata Wittgenstein, dan fakta-fakta ini tersusun dengan cara yang logis. Tujuan filsafat, bagi Wittgenstein muda, adalah mengembalikan bahasa ke bentuk logisnya, agar lebih baik menggambarkan bentuk logis dunia.
Karya-karya awal Wittgenstein mengilhami generasi positivis-logis—para pemikir analitis-kritis yang berangkat untuk menyanggah ‘pseudo-statements’ yang tak dapat diverifikasi dalam upaya untuk menentukan batas-batas bahasa yang bermakna. “Apa yang tak dapat kita bicarakan, kita mesti membiarkannya dalam diam”, Wittgenstein melantunkan kutipan tersebut di bagian penutup Tractatus. Untuk menjadi seorang filsuf, seseorang harus belajar menahan lidahnya. Positivisme logis adalah gerakan berpengaruh yang mendefinisikan bentuk filsafat analitik hingga tahun 1960-an. Akan tetapi, itu dilemahkan oleh karya orang yang sama yang menjadi pendirinya. Pada tahun 1930-an, Wittgenstein telah memutuskan bahwa The Picture Theory sungguh keliru. Dia mengabdikan sisa hidupnya untuk menjelaskan alasannya. “Beristirahat dengan kepuasan diri sama berbahayanya dengan beristirahat saat kau berjalan di salju”, ujarnya, “Kau tertidur dan mati dalam tidurmu” tambahnya.
Pergeseran pemikiran Wittgenstein, antara Tractatus dan Philosophical Investigations, memetakan pergeseran umum dalam filsafat abad ke-20 dari positivisme logis ke behaviorisme dan pragmatisme. Ini adalah pergeseran dari melihat bahasa sebagai struktur tetap yang dipaksakan pada dunia menjadi melihatnya sebagai struktur cair yang terikat-erat dengan praktik dan bentuk kehidupan kita sehari-hari. Bagi Wittgenstein, selanjutnya, membuat pernyataan yang bermakna bukanlah masalah memetakan bentuk logis dunia. Ini adalah masalah menggunakan istilah yang secara konvensional didefinisikan dalam ‘Tata Permainan Bahasa’ yang kita mainkan dalam kehidupan sehari-hari. “Dalam banyak kasus, arti sebuah kata adalah dari penggunaannya”, tulis Wittgenstein, dalam bagian paling terkenal di buku Philosophical Investigations. Bukan ‘apa’ yang kau katakan, melainkan cara kau mengatakannya, dan konteks di mana kau mengatakannya. Kata-kata adalah ‘bagaimana’ kau menggunakannya.
Komunikasi, dalam model ini, melibatkan penggunaan istilah-istilah konvensional dalam cara yang diakui oleh komunitas linguistik. Ini melibatkan suatu cara untuk memainkan tata permainan bahasa yang diterima secara konvensional.
“Jika seekor singa dapat berbicara, kita semestinya tak dapat memahaminya”, kata Wittgenstein, karena tata permainan bahasa singa terlalu berbeda dari “permainan” kita untuk memungkinkan pemahaman kita terhadapnya. Perlu dicatat, selain itu, teori Wittgenstein memungkinkan singa memiliki bahasa, yang didasarkan pada dinamika sosial dari aktivitas berburu dan kawin mereka. Auman dua singa jantan dewasa, yang menantang satu sama lain demi memimpin kawanan, dapat dikatakan sebagai aktivitas permainan bahasa seperti olok-olok dua manusia yang saling-saing, masing-masing berusaha mengalahkan yang lain melalui permainan kata-kata. Kita begitu jauh dari jalan pandangan formalistik bahasa yang dijelaskan dalam Tractatus. Kita telah meninggalkan ranah logika murni Platonis dan menemukan kembali dunia.
Pandangan Wittgenstein tentang bahasa sebagai praktik sosial sangat berguna bagi siapa saja yang ingin berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Para penulis dan komunikator selalu diberitahu untuk memikirkan audiens yang mereka ajak bicara dan menyusun komunike mereka sesuai dengan itu. Filsafat Wittgenstein mendorong sudut pandang ini—membawa kemudian melampaui linguistik ke dalam etnografi. Untuk berkomunikasi dengan suku sosial, dengarkan bagaimana mereka bermain dengan bahasa. Dalam banyak kasus, bahasa gaul, olok-olokan, dan lelucon bukanlah bentuk komunikasi 'sekunder' yang terstruktur dengan buruk, tetapi sarana kode untuk menyusun pertukaran tajam dalam suatu komunitas. Sebuah gambar, kata mereka, bernilai ribuan kata, tetapi lelucon yang tepat waktu dapat mengungkapkan pandangan dunia. Wittgenstein pernah berkata bahwa “karya kefilsafatan yang serius dan baik dapat ditulis seluruhnya terdiri dari lelucon”.
Lelucon bukanlah sesuatu yang berlangsung sebentar saja, pada saat itu saja. Lelucon-lelucon mungkin secara logis tidak koheren (ini yang sering membuatnya lucu), namun memainkan peran penting dalam permainan bahasa yang mengikat komunitas bersama.
Pandangan Wittgenstein tentang bahasa juga penting bagi siapa pun yang terlibat dalam filsafat. Diktum: “Dalam kebanyakan kasus, makna adalah penggunaan” berfungsi sebagai koreksi penting bagi impuls yang mendorong spekulasi metafisik tidak jelas yang didasarkan pada penyalahgunaan kata-kata. Ambil kata 'Tuhan', misalnya. Perdebatan kontemporer antara ateis dan teis (seseorang yang percaya Tuhan) didasarkan pada gagasan apakah kata 'Tuhan' merepresentasikan sesuatu yang nyata di dunia ataukah tidak sama sekali. Teis berpendapat bahwa kata tersebut merepresentasikannya (dan mengikat diri mereka dalam simpul semantik—mencoba untuk memverifikasi klaim ini), sementara ateis berpendapat sebaliknya. Namun, kedua pihak dalam perdebatan ini tanpa disadari mengandalkan The Picture Theory. Dalam teori ini, bahasa merepresentasikan fakta-fakta tentang dunia. Apa yang dikatakan hanya akan berakhir menjadi benar atau salah. Keduanya tidak akan pernah bertemu pada satu konvensi.
Pendekatan Wittgensteinian untuk perdebatan ini dimulai dengan menunjukkan bahwa 'Tuhan' adalah kata yang memiliki arti berbeda dalam konteks komunitas yang berbeda. Dalam konteks komunitas linguistik yang berbeda, orang-orang menggunakan kata 'Tuhan' dengan cara yang berbeda untuk mengartikulasikan aspek pengalaman yang berbeda-beda pula (pertimbangkan kalimat “Sekarang semuanya ada di tangan Tuhan” atau “Ketika matahari terbit, aku merasakan kehadiran Tuhan”). Dengan demikian, cara berpikir lain tentang makna 'Tuhan' adalah dengan melihat penggunaan istilah ini di orang-orang sebagai gerakan dalam permainan bahasa sosial—sebuah gerakan yang idealnya memiliki konotasi spesifik untuk anggota komunitas. Mungkin istilah 'Tuhan' tersebut mengungkapkan kesetiaan pada cara hidup, jalan hidup, seperti argumen Karen Armstrong. Mungkin mengungkapkan keheranan manusia di hadapan keberadaan. Intinya adalah bahwa menggunakan istilah tidak selalu menyiratkan kepercayaan pada entitas yang sesuai dengan istilah tersebut. Arti sebuah kata bergantung pada kegunaannya dalam konteks, bukan referensi idealnya di luar semua konteks yang memungkinkannya.
Ajaran Wittgenstein memiliki nilai praktikal. Mengapa membuang-buang waktu untuk memperdebatkan masalah yang tidak akan pernah terselesaikan ketika semuanya dapat dikempiskan dengan pertanyaan sederhana: “Apakah kita membicarakan hal yang sama?”. Jika kau berjuang untuk mengatasi dorongan untuk mendefinisikan sesuatu dengan terlalu hati-hati, atau menemukan diri kau sendiri terobsesi terhadap arti kata-kata dan definisi 'benar-nya', atau jika kau merasa yakin, seperti banyak filsuf, eksistensi kata secara logis menyiratkan beberapa esensi metafisik, atau bentuk Platonis, yang sesuai dengan kata ini, ingatlah bahwa apa yang memberi makna pada kata adalah wacana-sosial-konvensional di mana kata itu digunakan. Dengan memerhatikan konteks bahasa biasa yang memberi arti pada kata-kata, kita dapat menghindari penyalahgunaannya dan tak mencoba membuatnya menjadi hal-hal yang tidak dimaksudkan. Semakin kita mengembalikan kata-kata ke “rumah mereka”, melihatnya dalam konteks bahasa biasa tempat mereka bekerja, semakin mudah untuk melepaskan simpul-simpul dalam bahasa dan memahami apa yang sebenarnya dikatakan.
Sumber Literatur:
Meaning is use: Wittgenstein on the limits of language, Tim Rayner: https://philosophyforchange.wordpress.com/2014/03/11/meaning-is-use-wittgenstein-on-the-limits-of-language/
Thursday 27 October 2022
Nietzsche: Penggunaan dan Penyalahgunaan Sejarah (Esai Translasi)
Antara tahun 1873 dan 1876, Nietzsche menerbitkan buku Unfashionable Observations/Untimely Meditations/Thoughts Out of Season (bahasa Jerman: Unzeitgemässe Betrachtungen) yang terdiri dari empat karyanya. Bagian kedua dari bukunya ini adalah esai yang sering dialihbahasakan dan diberi judul “The Use and Abuse of History for Life/Penggunaan dan Penyalahgunaan Sejarah untuk Kehidupan” (1874). Namun, terjemahan yang lebih akurat dari karyanya tersebut adalah “On the Uses and Disadvantages of History for Life/Tentang Kegunaan dan Kerugian Sejarah untuk Kehidupan”.
Makna dari “Sejarah” dan “Kehidupan”
Dua istilah kunci dalam judul, “sejarah” dan “kehidupan” digunakan dalam cara yang sangat luas. Nietzsche secara khusus memaknai “sejarah” sebagai pengetahuan historis dari budaya-budaya sebelumnya (misalnya Yunani, Roma, Renaisans), yang mencakup pengetahuan tentang filsafat masa lampau, sastra, seni, musik, dan sebagainya. Tapi dia juga memikirkan pengetahuan secara umum, termasuk komitmen pada prinsip-prinsip ilmiah atau metode ilmiah yang ketat, dan juga kesadaran-diri terkait historisitas-umum yang terus-menerus menempatkan waktu dan budaya seseorang dalam kaitannya dengan orang lain yang telah datang sebelumnya.
Istilah “kehidupan” tidak didefinisikan dengan jelas di dalam esainya ini. Di satu titik, Nietzsche menggambarkannya sebagai “sebuah kegelapan mengemudikan kekuatan keinginan-diri yang tidak terpuaskan”, tetapi itu tidak banyak memberi tahu kita. Apa yang tampaknya paling sering dia pikirkan, ketika berbicara tentang “kehidupan”, adalah sesuatu seperti keterlibatan yang dalam, kaya, dan kreatif dengan dunia tempat seseorang tinggal. Di sini, seperti dalam semua tulisannya, penciptaan budaya yang mengesankan sangat penting bagi Nietzsche.
Apa yang Ditentang Nietzsche
Pada awal abad ke-19, Hegel (1770-1831) telah membangun filsafat sejarah yang melihat sejarah peradaban sebagai perluasan kebebasan manusia dan pengembangan kesadaran-diri yang lebih besar mengenai sifat dan makna sejarah. Filsafat Hegel sendiri merepresentasikan tahap tertinggi yang belum dicapai dalam pemahaman-diri manusia. Setelah Hegel, secara umum diterima bahwa pengetahuan tentang masa lalu adalah hal yang baik. Faktanya, abad kesembilan belas berbangga diri karena lebih terinformasi secara historis daripada zaman sebelumnya.
Nietzsche, bagaimanapun, seperti yang dia suka lakukan, mempertanyakan kepercayaan luas ini.
Dia mengidentifikasi 3 pendekatan terhadap sejarah: yang monumental, yang antikuarian, dan yang kritis. Masing-masing dapat digunakan dengan cara yang baik, tetapi masing-masing memiliki bahayanya sendiri.
Pendekatan Sejarah yang Monumental
Pendekatan ini berfokus pada contoh-contoh kebesaran manusia, individu yang “memperbesar konsep manusia … memberikan rasa puas yang lebih indah”. Nietzsche tidak menyebutkan nama, tetapi dia agaknya merujuk kepada orang-orang seperti Musa, Yesus, Pericles, Socrates, Caesar, Leonardo, Goethe, Beethoven, dan Napoleon. Satu hal yang sama-sama dimiliki oleh semua individu hebat adalah kesediaan yang angkuh untuk mempertaruhkan nyawa dan mengorbankan kesejahteraan materi mereka. Orang-orang seperti itu dapat menginspirasi kita untuk meraih kebesaran diri kita sendiri. Mereka adalah antidote keletihan-dunia.
Tapi pendekatan sejarah yang monumental membawa bahaya-bahaya tertentu. Ketika kita melihat tokoh-tokoh masa lalu ini sebagai inspirasi, kita mungkin mendistorsi sejarah dengan mengabaikan keadaan-keadaan unik yang memunculkannya. Sangat mungkin bahwa tidak ada figur seperti itu yang bisa muncul lagi karena keadaan seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Bahaya lain terletak pada cara dari beberapa orang yang memperlakukan pencapaian besar di masa lalu (misalnya tragedi Yunani, lukisan Renaisans) sebagai sesuatu yang kanonikal. Mereka dipandang memberi paradigma bahwa seni kontemporer tidak boleh menantang atau menyimpang dari konvensi seni yang sudah ada sejak masa lampau.
Ketika digunakan dengan cara ini, sejarah yang monumental dapat menghalangi jalan menuju pencapaian budaya yang baru dan orisinal.
Pendekatan Sejarah yang Antikuarian
Pendekatan ini mengacu pada pendalaman ilmiah dalam beberapa periode masa lalu atau budaya masa lalu. Ini adalah pendekatan sejarah yang khas akademisi. Berguna membantu kita untuk meningkatkan makna dari identitas suatu budaya. Misalnya, ketika penyair kontemporer memperoleh pemahaman mendalam tentang tradisi puitis tempat mereka berasal, ini memperkaya karya mereka sendiri. Mereka mengalami “kepuasan sebatang pohon dengan akar-akarnya”.
Akan tetapi, pendekatan ini juga memiliki kelemahan-kelemahan tersembunyi. Terlalu banyak tenggelam dalam masa lalu dengan mudah mengarah pada keterpesonaan yang tidak cerdik dan penghormatan terhadap apa pun yang lama, terlepas dari apakah itu benar-benar mengagumkan atau menarik. Pendekatan sejarah yang antikuarian dengan mudah merosot menjadi keterpelajaran belaka, di mana tujuan melakukan sejarah telah lama dilupakan. Dan pemujaan terhadap masa lalu dapat menghambat orisinalitas. Produk-produk budaya masa lalu dipandang begitu gemilang, sehingga kita hanya bisa berpuas diri dengannya dan tidak mencoba menciptakan sesuatu yang baru.
Pendekatan Sejarah yang Kritis
Pendekatan sejarah ini hampir berkebalikan dari pendekatan sejarah yang antikuarian. Alih-alih memuja masa lalu, sejarah yang kritis menolaknya sebagai bagian dari proses menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya, gerakan-artistik-orisinal seringkali sangat kritis dan penuh kritik terhadap gaya yang mereka coba gantikan (cara penyair Romantik menolak diksi buatan penyair abad ke-18). Bahayanya di sini, bagaimanapun, kita akan bersikap tidak adil terhadap masa lalu. Secara khusus, kita akan gagal untuk melihat bagaimana elemen-elemen dalam budaya masa lalu yang kita benci itu diperlukan; bahwa mereka adalah salah satu elemen yang melahirkan kita.
Masalah yang Disebabkan oleh Terlalu Banyak Pengetahuan Sejarah
Dalam pandangan Nietzsche, budaya Jerman/budaya Eropa/budayanya (dan dia mungkin akan mengatakan budaya kita juga) telah membengkak dengan terlalu banyak pengetahuan. Dan ledakan pengetahuan ini tidak melayani “kehidupan”—dengan kata lain, tidak mengarah pada budaya kontemporer yang lebih kaya, lebih bersemangat, lebih hidup. Di sisi lain, para akademisi terobsesi dengan metodologi dan analisis yang canggih. Dengan melakukan itu, mereka kehilangan tujuan sebenarnya dari apa yang mereka kerjakan. Mereka terus-menerus tidak sadar bahwa yang paling penting bukan apakah metodologi mereka masuk akal, tetapi apakah apa yang mereka lakukan berguna untuk memperkaya kehidupan dan budaya kontemporer ataukah tidak.
Seringkali terjadi—alih-alih mencoba menjadi kreatif dan orisinal, orang-orang terpelajar justru membenamkan diri dalam kegiatan ilmiah yang relatif kering. Hasilnya adalah kita hanya memiliki pengetahuan tentang budaya, bukannya memiliki budaya yang hidup. Alih-alih benar-benar mengalami sesuatu, kita mengambil sikap ilmiah yang terpisah dari sejarah itu sendiri. Orang-orang mungkin berpikir di sini, misalnya, perbedaan di antara lukisan atau komposisi musik, dan memperhatikan bagaimana itu mencerminkan pengaruh tertentu dari seniman atau komposer sebelumnya.
Di tengah-tengah esainya, Nietzsche mengidentifikasi lima kelemahan spesifik dari memiliki terlalu banyak pengetahuan sejarah. Sisanya merupakan elaborasi dari poin-poin ini. Lima kelemahan tersebut adalah:
Menciptakan terlalu banyak kontras antara apa yang ada di pikiran orang-orang dan cara mereka hidup. Misalnya, filsuf yang membenamkan dirinya dalam Stoikisme tidak lagi hidup seperti seorang Stoa; mereka hanya hidup seperti orang lain. Filsafatnya secara murni teoretis. Bukan sesuatu yang benar-benar dijalani.
Membuat kita berpikir bahwa kita lebih superior dari zaman sebelumnya. Kita cenderung melihat kembali periode-periode sebelumnya sebagai sesuatu yang lebih inferior dari kita dalam berbagai hal, terutama, mungkin, di bidang moralitas. Sejarawan modern bangga akan objektivitas mereka. Tapi jenis sejarah terbaik bukanlah jenis yang sangat objektif dalam pengertian ilmiah yang kering. Sejarawan terbaik bekerja seperti seniman yang membawa-menghidupkan zaman sebelumnya ke kehidupan kontemporer kita.
Mengganggu naluri-naluri dan menghambat perkembangan kedewasaan. Untuk mendukung gagasan ini, Nietzsche secara khusus mengeluhkan cara para akademisi modern yang terlalu cepat menjejalkan diri dengan terlalu banyak pengetahuan. Hasilnya adalah mereka kehilangan kedalaman. Spesialisasi ekstrem, ciri lain dari ilmu pengetahuan modern, menjauhkan mereka dari kebijaksanaan, yang membutuhkan pandangan yang lebih luas tentang berbagai hal.
Membuat kita menganggap bahwa diri kita adalah peniru yang lebih inferior dari pendahulu kita.
Mengarah pada ironi dan sinisme.
Dalam menjelaskan poin 4 dan 5, Nietzsche memulai kritiknya yang berkelanjutan terhadap Hegelianisme. Esai diakhiri dengan dia mengungkapkan harapan kepada “golongan muda”, yang sepertinya dia maksudkan karena mereka belum cacat oleh terlalu banyak pendidikan.
Di Latar Belakang – Richard Wagner
Dalam esai ini, Nietzsche tidak mengutip kawannya pada saat itu: komposer Richard Wagner. Tapi dalam menarik kontras antara mereka yang hanya tahu tentang budaya dan mereka yang secara kreatif terlibat dengan budaya, dia hampir pasti menganggap Wagner sebagai contoh dari tipe yang kedua. Pada saat itu, Nietzsche bekerja sebagai profesor, di Universitas Basel di Swiss. Basel merepresentasikan pengetahuan historis. Kapan pun dia bisa, dia akan naik kereta api ke Luzern untuk mengunjungi Wagner, yang pada saat itu sedang menyusun Der Ring des Nibelungen-nya. Rumah Wagner di Tribschen mewakili “kehidupan”. Bagi Wagner, jenius-kreatif yang juga seorang yang suka bertindak, terlibat penuh di dunia, dan bekerja keras untuk meregenerasi budaya Jerman melalui opera—mencontohkan bagaimana seseorang dapat menggunakan masa lalu (tragedi Yunani, legenda Nordik, musik klasik Romantik) dalam cara yang sehat untuk menciptakan sesuatu yang baru.
Artikel ditulis oleh Emrys Westacott, Ph.D dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Mochammad Aldy Maulana Adha.
Sunday 23 October 2022
Translasi Puisi-Puisi Baudelaire
Thursday 13 October 2022
A Little Fable - Kafka (Cerpen Translasi)
Tuesday 4 October 2022
Pengantar Singkat Eksistensialisme (Esai Translasi)
Eksistensialisme berfokus pada pertanyaan tentang keberadaan manusia & perasaan bahwa tak ada tujuan atau penjelasan mutlak mengenai inti keberadaan. Eksistensialisme, khususnya eksistensialisme-ateistik, berpendapat bahwa, (karena tidak ada Tuhan atau kekuatan transenden lain) satu-satunya cara untuk melawan “void” ini adalah dengan “merangkul” eksistensi kita sendiri.
Dengan demikian, Eksistensialisme percaya bahwa individu sepenuhnya bebas & harus mengambil tanggung jawab pribadi untuk diri mereka sendiri (walaupun dengan tanggung jawab ini muncul kecemasan, penderitaan, atau ketakutan yang mendalam). Oleh karenanya, ia menekankan tindakan, kebebasan, & keputusan sebagai hal yang mendasar, serta menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi kondisi kemanusiaan yang secara fundamental irasional (yang ditandai dengan penderitaan & kematian yang tak terhindarkan) adalah dengan menjalankan kebebasan & mengambil pilihan-pilihan pribadi kita (penolakan Determinisme sepenuhnya).
Seringkali, Eksistensialisme (sebagai sebuah gerakan) digunakan untuk menggambarkan mereka yang menolak untuk menjadi bagian dari aliran pemikiran mana pun, menolak kecukupan suatu korpus kepercayaan atau sistem apa pun—mengklaim korpus-korpus tersebut dangkal, akademis, & jauh dari kehidupan. Meskipun memiliki banyak kesamaan dengan Nihilisme, Eksistensialisme lebih merupakan reaksi terhadap filsafat tradisional, seperti Rasionalisme, Empirisme, & Positivisme, yang berusaha menemukan tatanan tertinggi & makna universal dalam prinsip-prinsip metafisik atau dalam struktur dunia yang diamati. Ini menegaskan bahwa manusia benar-benar membuat keputusan berdasarkan apa yang berarti bagi mereka, ketimbang pada apa yang rasional.
Eksistensialisme berasal dari filsuf abad ke-19—Søren Kierkegaard (1813 - 1855) & Friedrich Nietzsche (1844 - 1900)—meskipun keduanya tak menggunakan istilah eksistensialisme secara gamblang di dalam karya-karya mereka. Pada tahun 1940-an & 1950-an, eksistensialis Prancis seperti Jean-Paul Sartre (1905 - 1980), Albert Camus (1913 - 1960), & Simone de Beauvoir (1908 - 1986) menulis karya ilmiah & karya fiksi yang mempopulerkan tema-tema eksistensial, seperti ketakutan, kebosanan, keterasingan, absurditas, kebebasan, komitmen, kehampaan, & ketiadaan.
Keyakinan Utama
Tak seperti René Descartes (1596 - 1650), yang mengagungkan kesadaran, Eksistensialis menegaskan bahwa manusia “dilemparkan ke” semesta yang konkret, alam semesta tetap yang tak dapat “dipikirkan lebih jauh”, & oleh karenanya eksistensi (“berada di dunia”) mendahului kesadaran, & itu merupakan realitas tertinggi. Maka, eksistensi ada sebelum esensi (esensi adalah makna yang dapat dianggap berasal dari kehidupan)—kontras dengan pandangan filsafat tradisional yang berasal dari Yunani kuno. Seperti yang dikatakan Sartre: “Pada mulanya [manusia] bukan apa-apa. Hanya setelah itu dia akan menjadi sesuatu, dan dia sendiri akan membuat dirinya menjadi apa yang dia inginkan.”
Kierkegaard melihat rasionalitas sebagai mekanisme yang digunakan manusia untuk melawan kecemasan eksistensial mereka, ketakutan mereka (ketika) berada di dunia. Sartre melihat rasionalitas sebagai bentuk “itikad buruk”, upaya diri untuk memaksakan struktur pada dunia fenomena yang secara fundamental irasional & random. Itikad buruk ini menghalangi kita untuk menemukan makna dalam kebebasan, & membatasi kita dalam pengalaman sehari-hari.
Kierkegaard juga menekankan bahwa seorang individu harus memilih jalan mereka sendiri tanpa bantuan standar-objektif-yang-universal. Nietzsche lebih lanjut berpendapat bahwa seorang individu harus memutuskan situasi mana yang dianggap sebagai situasi moral. Dengan demikian, sebagian besar Eksistensialis percaya bahwa pengalaman pribadi & bertindak berdasarkan keyakinannya sendiri sangatlah penting dalam mencapai kebenaran, & bahwa pemahaman situasi oleh seseorang yang terlibat langsung dalam situasi itu jelas lebih unggul ketimbang pemahaman pengamat objektif yang tak mengalami situasi tersebut (mirip dengan konsep Subjektivisme).
Menurut Camus, ketika kerinduan seorang individu akan keteraturan bertabrakan dengan ketakteraturan di dunia kenyataan, hasilnya adalah absurditas. Oleh karenanya, manusia adalah subjek dalam alam semesta yang masa bodoh, ambigu, & absurd—di mana makna tak disediakan oleh tatanan alam, melainkan (dapat) diciptakan (namun hanya sementara & tak stabil) oleh tindakan & interpretasi manusia.
Eksistensialisme dapat bersifat ateistik, teologis (atau teistik), atau agnostik. Beberapa Eksistensialis, seperti Nietzsche, menyatakan bahwa “Tuhan telah mati” & bahwa konsep Tuhan sudah usang. Figur yang lain, seperti Kierkegaard, sangat religius, bahkan jika para eksistenialis-ateistik merasa tak bisa membenarkan anggapan tersebut. Faktor penting bagi Eksistensialis adalah kebebasan memilih “untuk percaya” atau “tak percaya”.
Sejarah Eksistensialisme
Tema-tema bercorak eksistensialis muncul dalam tulisan-tulisan Buddhis & Kristen awal (termasuk tulisan St. Augustine & St. Thomas Aquinas). Pada abad ke-17, Blaise Pascal (1623 - 1662) menyatakan bahwa, tanpa tuhan, hidup tak akan bermakna, membosankan & penuh kesengsaraan, seperti yang diyakini oleh para Eksistensialis, meskipun, tak seperti mereka—Pascal melihat ini sebagai alasan dari eksistensi tuhan. Seseorang yang hampir sezaman dengannya, John Locke (1632 - 1704), menganjurkan otonomi individu & determinasi-diri, tetapi dalam pengejaran Liberalisme & Individualisme mutlak— ketimbang sebagai tanggapan atas pengalaman Eksistensialis.
Eksistensialisme, dalam bentuknya yang saat ini dapat dikenali—mula-mula diilhami oleh filsuf Denmark abad ke-19 Søren Kierkegaard, filsuf Jerman Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger (1889 - 1976), Karl Jaspers (1883 - 1969) & Edmund Husserl (1859 - 1938)—juga penulis seperti Fyodor Dostoevsky dari Rusia (1821 - 1881) & Franz Kafka dari Ceko (1883 - 1924). Dapat dikatakan bahwa Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) & Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) juga berpengaruh besar dalam perkembangan Eksistensialisme, karena filsafat Kierkegaard & filsafat Nietzsche ditulis sebagai tanggapan atau pertentangan terhadap mereka.
Kierkegaard & Nietzsche, seperti Pascal sebelumnya, tertarik pada apa yang orang-orang sembunyikan tentang ketakbermaknaan hidup & penggunaan “pengalihan” untuk melarikan diri dari rasa jemu. Namun, tak seperti Pascal, mereka menganggap peran membuat-pilihan-bebas pada nilai-nilai fundamental & keyakinan penting dalam upaya untuk mengubah sifat & identitas “pembuat-pilihan” tersebut. Dalam kasus Kierkegaard, ini menghasilkan “ksatria-iman”, yang menaruh kepercayaan penuh pada dirinya sendiri & pada tuhan, seperti yang dijelaskan dalam karyanya tahun 1843 “Fear and Trembling”. Dalam kasus Nietzsche—yang banyak difitnah—yaitu “Übermensch” (atau “Superman”)—mencapai superioritas & transendensi tanpa menggunakan “keduniawian-lain” à la Kekristenan, dalam bukunya “Thus Spake Zarathustra” (1885) & “Beyond Good and Evil” (1887).
Martin Heidegger adalah seorang filsuf awal yang penting dalam gerakan tersebut, khususnya karyanya yang berpengaruh pada tahun 1927 “Being and Time”, meskipun ia sendiri dengan keras menyangkal menjadi seorang eksistensialis dalam pengertian Sartrean. Diskursusnya tentang ontologi berakar pada analisis mode keberadaan individu manusia, & analisisnya tentang otentisitas & kecemasan dalam budaya modern membuatnya sangat Eksistensialis.
Eksistensialisme muncul pada pertengahan abad ke-20, sebagian besar melalui karya ilmiah & karya fiksi dari Eleksistensialis Prancis, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, & Simone de Beauvoir. Maurice Merleau-Ponty (1908 - 1961) adalah eksistensialis Prancis yang berpengaruh & sering diabaikan pada periode itu.
Sartre mungkin yang paling terkenal, serta salah satu dari sedikit eksistensialis yang benar-benar menerima disebut “eksistensialis”. “Being and Nothingness” (1943) adalah karyanya yang paling penting, & novel serta dramanya, termasuk “Nausea” (1938) & “No Exit” (1944), membantu mempopulerkan gerakan ini.
Dalam “The Myth of Sisyphus” (1942), Albert Camus menggunakan analogi mitos Yunani Sisyphus (yang dikutuk selamanya untuk mendorong batu ke atas bukit, hanya untuk menggulingkannya ke bawah lagi) sebagai contoh kesia-siaan eksistensi, tetapi menunjukkan bahwa Sisyphus akhirnya menemukan makna & tujuan dalam hidupnya, hanya dengan terus-menerus “menerapkan dirinya” untuk itu.
Simone de Beauvoir, seorang eksistensialis penting yang menghabiskan sebagian besar hidupnya bersama Sartre, menulis tentang feminis & etika eksistensial dalam karya-karyanya, termasuk “The Second Sex” (1949) & “The Ethics of Ambiguity” (1947).
Meskipun Sartre dianggap (oleh sebagian besar) sebagai Eksistensialis yang paling unggul, & (oleh banyak orang) sebagai filsuf penting & inovatif dalam dirinya sendiri, yang lain kurang terkesan dengan kontribusinya. Heidegger sendiri berpikir bahwa Sartre hanya mengambil karyanya & meregresinya kembali ke filsafat berorientasi subjek-objek Descartes & Husserl, yang persis seperti apa yang Heidegger coba bebaskan dari filsafat. Beberapa orang melihat Maurice Merleau-Ponty sebagai filsuf Eksistensialis yang lebih baik, khususnya karena penggabungannya dengan tubuh sebagai cara kita mengada di dunia, & untuk analisis “persepsi” yang lebih lengkap (dua bidang di mana karya Heidegger sering dianggap kurang).
Kritik terhadap Eksistensialisme
Herbert Marcuse (1898 - 1979) mengkritik Eksistensialisme, terutama “Being and Nothingness” karya Sartre, karena memproyeksikan beberapa fitur hidup dalam masyarakat modern yang menindas (fitur seperti kecemasan & ketakberarmaknaan) ke dalam sifat keberadaan itu sendiri.
Roger Scruton (1944 - 2020) mengklaim bahwa baik konsep Heidegger tentang ketakotentikan & konsep itikad buruk Sartre sama-sama tak konsisten, dalam arti bahwa mereka menyangkal setiap kredo moral yang universal, namun berbicara tentang konsep-konsep ini seolah-olah setiap orang terikat untuk mematuhinya.
Kaum Marxis, khususnya ketika pascaperang Prancis, menemukan Eksistensialisme bertentangan dengan penekanan mereka pada solidaritas umat manusia & teori determinisme ekonomi. Mereka lebih lanjut berpendapat bahwa penekanan Eksistensialisme pada pilihan individu mengarah pada kontemplasi daripada tindakan, & bahwa hanya kaum borjuis yang memiliki kemewahan untuk menjadikan diri mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan melalui pilihan mereka, sehingga mereka menganggap Eksistensialisme sebagai filsafat borjuis.
Kritikus Kristen mengeluhkan bahwa Eksistensialisme menggambarkan umat manusia dalam cahaya terburuk, mengabaikan martabat & anugerah yang berasal dari penciptaan menurut Imago Dei. Juga, menurut kritikus Kristen, Eksistensialis tak dapat menjelaskan dimensi moral kehidupan manusia, & tak memiliki dasar teori etika jika mereka menyangkal bahwa manusia terikat oleh perintah tuhan. Di sisi lain, beberapa penafsir telah keberatan dengan penggolongan Kierkegaard yang terus-menerus pada Kekristenan, terlepas dari ketakmampuannya untuk secara efektif menjustifikasinya.
Dalam istilah yang lebih umum, penggunaan karakter pseudonim dalam tulisan eksistensialis dapat membuatnya tampak seperti pengarang yang tak mau mengakui “insight”-nya sendiri, & membingungkan filsafat dengan sastra.
*****
Sumber Literatur
Mastin, Luke. "Existentialism - By Branch / Doctrine - The Basics of Philosophy." Existentialism - The Basics of Philosophy: https://www.philosophybasics.com/branch_existentialism.html
Tuesday 20 September 2022
Apa yang Nietzsche Maksud ketika Mengatakan “Tuhan telah Mati” (Esai Translasi)
“Tuhan telah mati!”
Dalam bahasa Jerman, Gott ist tot! adalah ungkapan yang paling lekat dikaitkan kepada Nietzsche. Namun ada ironi di sini karena Nietzsche bukanlah orang pertama yang mengemukakannya. Penulis Jerman, Heinrich Heine (yang Nietzsche kagumi), mengatakannya lebih dulu. Tapi Nietzsche sebagai seorang filsuf memiliki misi pribadi untuk menanggapi pergeseran budaya yang dramatis dengan ungkapan “Tuhan telah mati”.
Ungkapan tersebut pertama kali muncul di awal Book Three dari The Gay Science (1882). Kemudian ungkapan itu menjadi ide sentral dalam aforisme masyhur (125) berjudul Orang Gila, yang dimulai dengan:
“Pernahkah kau mendengar tentang orang gila yang menyalakan lentera di pagi hari yang cerah, yang berlari ke pasar, dan menangis tanpa henti: “Aku mencari Tuhan! Aku mencari Tuhan!”—Karena banyak dari mereka yang tak percaya pada Tuhan berdiri di sekitarnya saat itu, dia memancing banyak tawa. Apakah dia tersesat? Tanya seseorang. Apakah dia tersesat seperti anak kecil? Tanya yang lain. Atau dia sedang bersembunyi? Apakah dia takut kepada kita? Apakah dia sudah melakukan perjalanan? Mengungsi ke negeri lain?—Sehingga mereka berteriak-teriak dan tertawa.
Orang gila itu melompat ke tengah-tengah mereka dan menusuk mereka dengan matanya. “Di mana Tuhan?” dia menangis; “Aku akan memberitahumu. Kita telah membunuhnya—kau dan aku. Kita semua adalah pembunuhnya. Tapi bagaimana kita melakukan ini? Bagaimana kita bisa meminum lautan? Siapa yang memberi kita lap serap untuk menghapus seluruh cakrawala? Apa yang kita lakukan ketika kita melepaskan rantai bumi dari mataharinya? Ke mana ia bergerak sekarang? Ke mana kita bergerak? Jauh dari seluruh matahari? Bukankah kita terus-menerus menyelam? Mundur, ke samping, ke depan, ke segala arah? Apakah masih ada yang naik? Atau turun? Apakah kita tak tersesat, seperti melalui ketiadaan yang tak terbatas? Apakah kita tak merasakan napas dari ruang hampa? Bukankah semakin dingin? Bukankah malam terus-menerus mendekati kita? Apakah kita tak perlu menyalakan lentera di pagi hari? Apakah kita belum mendengar suara penggali kubur yang mengubur Tuhan? Apakah kita belum mencium bau busuk ilahi? Dewa-dewi juga membusuk. Tuhan telah mati. Tuhan tetap mati. Dan kita telah membunuhnya.”
Orang gila terus berkata
“Tak pernah ada tindakan yang lebih besar; dan siapa pun yang lahir setelah kita—demi tindakan ini, ia akan menjadi bagian dari sejarah yang lebih tinggi dari semua sejarah sampai saat ini.” Ditemui oleh ketidakpahaman, ia menyimpulkan:
“Aku datang terlalu dini … Peristiwa luar biasa ini masih dalam perjalanan, masih berkeliaran; itu belum sampai ke telinga seorang manusia. Petir dan guntur membutuhkan waktu; cahaya bintang membutuhkan waktu; tindakan-tindakan, meskipun dilakukan, masih membutuhkan waktu untuk dilihat dan didengar. Tindakan ini masih lebih jauh dari mereka ketimbang bintang yang paling jauh—namun mereka telah melakukannya sendiri.”
Apa maksud dari semua ini?
Hal pertama yang cukup jelas dan menjadi poin adalah bahwa pernyataan “Tuhan telah mati” adalah paradoks. Tuhan, secara definitif, itu abadi dan mahakuasa. Dia bukanlah entitas yang bisa mati. Jadi apa maksud dari ungkapan bahwa Tuhan telah “mati”? Gagasannya beroperasi pada beberapa tingkatan.
Bagaimana agama kehilangan tempatnya dalam budaya kita
Maksud yang paling jelas dan penting hanyalah ini: Dalam peradaban Barat, agama pada umumnya, dan Kekristenan, khususnya, berada dalam kemerosotan yang tidak dapat diubah. Ia kehilangan atau telah kehilangan tempat sentral yang telah dipegangnya selama dua ribu tahun terakhir. Ini berlaku di setiap bidang: dalam politik, filsafat, sains, sastra, seni, musik, pendidikan, kehidupan sosial sehari-hari, dan dalam kehidupan spiritual dari batin setiap individu.
Seseorang mungkin keberatan: namun, tentu saja, masih ada jutaan orang di seluruh dunia, termasuk Barat, yang masih sangat religius. Ini tidak diragukan lagi benar, tetapi Nietzsche tidak menyangkalnya. Dia menunjuk ke tren yang sedang berlangsung yang, seperti yang dia tunjukkan, kebanyakan orang belum sepenuhnya memahami. Tapi trennya tetap tidak terbantahkan.
Di masa lalu, agama sangat penting dalam budaya kita. Musik terhebat, seperti Bach – Mass In B Minor, bersifat religius dalam segi inspirasi. Karya seni terbesar dari Renaissance, seperti The Last Supper karya Leonardo da Vinci, secara khusus bertema keagamaan. Ilmuwan seperti Copernicus, Descartes, dan Newton, adalah orang-orang yang sangat religius. Gagasan ketuhanan memainkan peran kunci dalam pemikiran para filsuf seperti Aquinas, Descartes, Berkeley, dan Leibniz. Seluruh sistem pendidikan diatur oleh gereja. Sebagian besar orang dibaptis, menikah dan dimakamkan oleh gereja, dan menghadiri gereja secara teratur sepanjang hidup mereka.
Tidak satu pun dari hal-hal di atas benar lagi adanya. Kehadiran di gereja di sebagian besar negara Barat telah jatuh ke dalam jumlah yang sedikit, sekitar sembilan orang bahkan kurang. Sekarang banyak individu lebih menyukai upacara yang sekuler, yang tidak bersifat keagamaan saat perayaan kelahiran, pernikahan, dan kematian. Dan di antara para intelektual—ilmuwan, filsuf, penulis, dan seniman—kepercayaan agama hampir tidak berperan dalam pekerjaan dan karya-karya mereka.
Apa penyebab kematian Tuhan?
Jadi ini adalah alasan pertama dan paling mendasar di mana Nietzsche berpikir bahwa Tuhan telah mati. Budaya kita menjadi semakin sekuler. Alasannya tidak sulit untuk dipahami. Revolusi ilmiah yang dimulai pada abad ke-16 segera menawarkan cara untuk memahami fenomena alam yang terbukti jelas lebih unggul daripada upaya untuk memahami alam dengan mengacu pada prinsip-prinsip agama atau kitab suci. Tren ini mengumpulkan momentum dengan Era Pencerahan di abad ke-18 yang mengonsolidasikan gagasan bahwa alasan dan bukti harus menjadi dasar keyakinan kita ketimbang kitab suci atau tradisi. Dikombinasikan dengan industrialisasi pada abad ke-19, kekuatan teknologi yang berkembang pesat yang dilepaskan oleh ilmu pengetahuan, juga memberi orang-orang semacam rasa kontrol yang lebih besar atas alam. Merasa tidak berdaya melawan kekuatan irasional juga memainkan perannya dalam mengikis keyakinan beragama.
Pemaknaan lebih lanjut “Tuhan telah Mati!”
Seperti yang dijelaskan Nietzsche di bagian lain The Gay Science, klaimnya bahwa Tuhan telah mati bukan hanya klaim tentang kepercayaan agama. Dalam pandangannya, banyak dari pola pikir kita yang secara standar membawa unsur-unsur agama yang tidak kita sadari. Misalnya, sangat mudah untuk berbicara tentang alam seolah-olah alam mengandung makna dan tujuan. Atau jika kita berkata alam semesta seperti sebuah mesin yang hebat, metafora ini membawa implikasi yang halus bahwa mesin itu dirancang oleh seseorang. Mungkin yang paling mendasar dari semuanya adalah asumsi kita bahwa ada yang namanya kebenaran objektif. Yang kita maksud dengan ini adalah sesuatu seperti cara dunia akan digambarkan dari “sudut pandang mata tuhan”—sudut pandang yang tidak hanya di antara banyak perspektif, tetapi adalah Satu Perspektif Sejati yang tunggal. Bagi Nietzsche, semua ilmu pengetahuan harus berangkat dari perspektif yang terbatas.
Implikasi dari kematian Tuhan
Selama ribuan tahun, gagasan tentang Tuhan (atau para dewa-dewi) telah menjadi jangkar bagi pemikiran kita terhadap dunia. Ini sangat penting sebagai landasan moralitas. Prinsip-prinsip moral yang kita ikuti (Jangan membunuh. Jangan mencuri. Membantu mereka yang membutuhkan, dll.) mengandung otoritas agama di belakangnya. Dan agama memberikan motif untuk mematuhi aturan-aturan ini, karena agama memberi tahu kita bahwa kebajikan akan dihargai dan yang sebaliknya akan dihukum. Apa yang terjadi jika permadani ini ditarik?
Nietzsche tampaknya berpikir bahwa respons pertama adalah kebingungan dan kepanikan. Seluruh bagian Orang Gila yang dikutip di atas penuh dengan pertanyaan menakutkan. Turun ke dalam kekacauan dipandang sebagai salah satu kemungkinan. Tapi Nietzsche melihat kematian Tuhan sebagai bahaya besar dan peluang besar. Ini memberi kita kesempatan untuk membangun “tabel nilai” yang baru, yang akan mengungkapkan cinta yang baru ditemukan dari dunia ini dan kehidupan ini. Karena salah satu keberatan utama Nietzsche terhadap Kekristenan adalah bahwa dengan memikirkan kehidupan ini hanya sebagai persiapan untuk kehidupan setelah kematian, sehingga pada akhirnya keagamaan merendahkan nilai kehidupan itu sendiri.
Maka, setelah kecemasan besar yang diungkapkan dalam Book III, Book IV dari The Gay Science adalah ekspresi mulia dari pandangan yang mengafirmasi kehidupan.
Artikel ditulis oleh Emrys Westacott, Ph.D dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Mochammad Aldy Maulana Adha.
Filosofi Keputusasaan à la Cioran (Esai Translasi)
Aku sendirian di pekuburan yang menghadap ke desa ketika seorang wanita hamil datang ke sini. Aku segera pergi, supaya tidak melihat pembawa mayat wanita ini dari jarak dekat, atau untuk merenungkan kontras antara rahim yang agresif dan pusara yang usang—antara janji-janji ilusif dan akhir dari semua omong kosong ini. (Cioran, 1998)
Jika benar bahwa dengan kematian kita sekali lagi menjadi seperti sebelumnya, bukankah lebih baik untuk mematuhi kemungkinan murni itu, tidak bergerak darinya? Apa gunanya jalan memutar ini, ketika kita mungkin tetap selamanya dalam keterpenuhan yang tidak disadari? (Cioran, 1998)
Kita tidak terburu-buru menuju kematian, kita melarikan diri dari malapetaka kelahiran, para penyintas berjuang untuk melupakannya. Ketakutan akan kematian hanyalah proyeksi ke masa depan dari ketakutan yang berasal dari momen pertama kehidupan kita. Tentu saja, kita enggan menganggap kelahiran sebagai momok: bukankah hal itu telah ditanamkan dalam diri kita sebagai kebaikan yang berkuasa—tidakkah kita diberitahu bahwa yang terburuk datang terakhir, bukan pada awal kehidupan kita? Namun kejahatan, kejahatan yang sebenarnya, ada di belakang, bukan di depan kita. Apa yang luput dari Yesus tidak luput dari Buddha: “Jika tiga hal tidak ada di dunia, o para murid, Yang Sempurna tidak akan hadir di dunia ...” Dan di hadapan usia tua dan kematian, Sang Buddha menempatkan fakta kelahiran, sumber dari setiap kelemahan, setiap bencana. (Cioran, 1998).